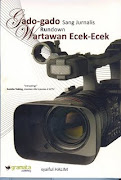Malam itu, di tengah upacara mabbissu, tiba-tiba wajah Puang Matoa Bissu Saidi tercekat dan berpeluh. Ia meringis, sembari tangan kirinya mencoba menjangkau tiang tengah rumah. Tangannya yang satu lagi masih memegang hulu keris yang ujungnya menembus perut tetua bissu ini. Bissu yang lain tampak terkejut. Puang Matoa dengan keris masih menghunjam tubuhnya, kemudian berbalik, masuk ke dalam kamar arajang (altar).
Setelah sekian lama, ia keluar lagi. Keris itu masih tetap tertancap. Ketika Puang Matoa mencabutnya dengan sedikit memaksa, menyemburatlah cairan merah membasahi baju bissu keemasannya. Darah segar sepanjang kira-kira 7 cm itu menggumpal di ujung keris, dan segera dijilati oleh Puang Matoa. “Kejadian ini sering dialami oleh Puang Matoa, kalau syarat dalam melakukan upacara Mabbissu tidak lengkap,” ujar Amrullah, aktivitis LSM yang selama ini peduli masalah Bissu.
Dua jam sebelum peristiwa tersebut, di atas rumahnya yang tidak jauh dari Pasar Sentral Pangkep, Puang Saidi dengan pakaian putih-putih sibuk mengatur segala peralatan upacara dan sesajian yang akan dilakukakanya malam itu. Handphone bermerek yang dimilikinya selalu berbunyi. Dari pembicaraan yang terdengar, tampaknya ia sedikit marah. Ia bahkan mengancam seorang bissu di ujung telepon, agar segera datang. Bissu yang diteleponnya itu diperlukan kedatangannya untuk melengkapi syarat minimal jumlah bissu, agar upacara yang akan diadakan sebentar lagi bisa dimulai.
Sementara itu, Muharram, bissu termuda yang baru berusia 17 tahun tampak kecut di sudut ruangan. Ia lupa memakai tutup kepala dan masih berpakaian perempuan. Jemari tangannya bergetar saat menyusun tumpukan ketan tiga warna. Beberapa kali Puang Saidi memukul tangan Muharram ketika ia salah menyusun tumpukan ketan tersebut. Masse, bissu tertua yang ada di dalam ruangan tersebut, juga tampak tegang. Sesekali ia melongok ke luar jendela, berharap satu orang bissu yang sejak tadi ditunggu segera datang untuk meredakan kemarahan Puang Saidi. Namun yang ditunggu tidak juga muncul. Maka jadilah malam itu upacara mabbisu yang telah dijanjikannya tetap dilanjutkan, meski jauh dari syarat minimal.
Tidak seperti biasa, mereka tampak tegang. Kami para tamu yang tidak tahu menahu tentang soal itu malah duduk dengan tenang dan nyaman.
Lima belas menit pertama, Puang Saidi dan tiga orang bissu dengan pakaian berwarna keemasan dengan bilah-bilah keris panjang menari memutari sesajian di tengah ruangan. Alunan mantra mitis yang menggunakan bahasa To Rilangi – sejenis bahasa kuno Bugis yang hanya dimengerti oleh komunitas Bissu dalam memimpin upacara sakral – mengalun ditingkahi gendang. Ketika alunan gendang semakin keras dan cepat, gerakan para bissu tersebut semakin melambat. Terlihat jelas mereka mulai trance.
Muharram, sang bissu muda, kemudian mulai membuka gerakan maggiri yang pertama. Keris panjang yang terselip di pinggangnya dilepaskannya, dengan gerakan pelan mengikuti irama gendang. Keris tersebut ditancapkannya ke telapak tangannya. Walau ditekan berkali-kali dengan keras, keris itu tidak juga bisa merobek telapak tangannya. Bahkan ketika ia dibaringkan di tengah ruangan dan Puang Saidi kemudian menancapkan keris ke tenggorakannya, tak sedikit pun kulit leher Muharram tergores. Kuatnya tekanan keris Puang Saidi ke leher Muharram ditunjukkan dengan bunyi berderak pada tiang sandaran. Seketika saya bergidik. Para Bissu yang dalam kesehariannya feminim itu, tiba-tiba malam itu tampak gagah, jauh dari kesan lemah-lembut yang lekat dengan kehidupan kesehariannya.
Di tengah ruangan, upacara mabbissu semakin liar. Para bissu muda kemudian menyingkir ke sudut ruangan, menjaga dupa agar terus menyala. Tepat ketika harum cendana semakin menguat, Puang Saidi melangkah ke depan. “Adengan ini hanya untuk bissu yang sudah senior. Yang muda belum diizinkan untuk melakukannya,” ujar Amrullah menjelaskan.
Bersama dengan Puang Saidi, Masse ikut berputar-putar. Ia tampak gagah. Ia meletakkan keris ke lantai rumah, dengan ujung keris yang menghunus ke atas. Lalu Masse menjatuhkan dirinya ke ujung keris itu. Alas kayu yang dijadikan tumpuan kerisnya berderak patah. Gerakan ini ia lakukan berulang-ulang. Bahkan beberapa kali ia menjatuhkan dirinya dengan sangat keras.
Keramaian bertambah ketika dengan keris terhunus, Puang Saidi menggorok lehernya sendiri. Ia lalu menyandarkan ujung keris tersebut ke tiang rumah, dan menekan-nekankan keris tersebut ke lehernya. Bunyi gendang semakin kuat. Puang Matoa Saidi melenguh, ia kemudian menancapkan keris panjangnya ke bagian perut. Ia menghentakkannya ke lantai, dan seketika bambu yang menjadi alas kersinya patah. Ia semakin liar. Namun, ketika ia bangkit dan menghujamkan kembali keris ke perutnya, matanya mendelik. Masse dan Muharram di sudut ruangan memucat wajahnya. Puang Saidi sempoyongan, dengan langkah tertatih ia berbalik ke dalam ruangan. Bunyi gendang terhenti. Kami tersenyum puas dan bertepuk tangan. Namun, sekembali dari ruangan, Puang Saidi ternyata masih memegang hulu keris yang masih menghujam ke perutnya, berkali-kali jempol tangan yang telah diludahinya diusapkan ke bagian perut. Kami tercekat, perut Puang Saidi berdarah. Terlihat darah segar!
Satu minggu sebelum perisitiwa tersebut, kami telah melakukan survey kecil-kecilan tentang bissu dan tradisinya di Kabupaten Pangkep. Kami memilih komunitas bissu di daerah itu sebab keberadaannya sebagai salah satu kelompok bissu di Sulawesi Selatan cukup kuat. Kelompok bissu di Pangkep merupakan kelompok Bissu Dewata, yang secara hierarkis merupakan kelompok bissu dengan tugas religius yang penting. Kelompok bissu yang lain tersebar di Kabupaten Soppeng, Wajo dan Bone. Komunitas bissu di Soppeng dikenal dengan nama Bissu Pattudang, di Wajo disebut Bissu Paddupa, sedangkan di Bone disebut dengan Bissu Mappakasengeng. Nah pimpinan dari semua kelompok bissu tersebut bergelar Puang Matoa, yang saat ini dipimpin oleh Puang Matoa Saidi dari kelompok Bissu Dewata, Segeri, Pangkep.
Catatan arkeologis menguatkan bahwa komunitas bissu memiliki fungsi yang cukup penting dalam struktur kerajaan di Sulawesi Selatan pada masa lalu. Sisa-sisa makam bissu dan sumur bissu di berbagai daerah, semisal di Bulukumba, Sindenreng, Bantaeng dan Luwu, masih bisa ditemukan walaupun komunitas di daerah itu sudah tidak lagi mengenal bissu dan tradisinya. Hal itu terkait dengan penghancuran bissu beserta simbol-simbolnya oleh gerakan DI/TII.
Walaupun diberangus, bissu-bissu tua dalam penyamaran dan pelariannya tetap mempraktekkan “kebissuannya” secara diam-diam dan tetap melakukan proses pengkaderan. Puang Saidi misalnya, merasakan pengalaman terusir dari rumah dan lari berpindah-pindah dari Pangkep, Soppeng dan Bone. Ia menjadi bissu ketika berumur 25 tahun, tepatnya tahun 1974. Ia dididik oleh Sanro Saide (alm), seorang Puang Matoa Bissu yang tersisa. Dalam kehidupannya, ia mengalami operasi pemberantasan "penyakit masyarakat" oleh salah satu instansi dengan sandi “operasi tobat”. Namun ia berhasil lolos dari peristiwa tersebut.
Bissu mulai terlupakan oleh publiknya sendiri justru di tanah kelahirannya. Namun lewat catatan para peneliti asing, mulai zaman Mathes pada abad 19, sampai pada masa Pelras, Andaya, Gilbert Hamonic serta banyak peneliti lainnya, bissu mulai dikenal kembali. Ketertarikan mereka disebabkan karena bissu merupakan jejak dari agama-agama orang Bugis kuno yang bersumber dari ajaran La Galigo. Karena itu, sampai saat ini, bissu seperti Puang Saidi paling tidak mengenal tiga varian bahasa Bugis kuno, yakni bahasa To Rilangi (bahasa Bugis sakral untuk dewa), bahasa La Galigo (bahasa Bugis kuno) dan bahasa Bugis yang awam seperti saat ini.
Uniknya, walaupun dari banyak sumber peneliti menyebut mereka sebagai kelanjutan agama kuno orang Bugis jauh sebelum agama Islam dikenal, namun Puang Saidi akan sangat marah jika disebutkan bahwa upacara mabbisu merupakan bagian dari musyrik. Bahkan ketika ia mencoba menjelaskan makna cermin, ia mempersamakannya dengan istilah Nur Muhammad yang kerap digunakan oleh para sufi Islam. “Itu merupakan sinkritisme antara ajaran leluhur dan agama Islam di Sulawesi Selatan. Sekaligus membuktikan bahwa Islam ketika kali pertama datang telah merupakan bagian dari adat, simbolisasi betapa adat dan agama melebur menjadi satu yang kemudian menjadi bagian dari kebudayaan di Sulawesi Selatan,” jelas Halilintar Latief, salah satu pakar Bissu.
Lewat Halilintar pula, pada tahun 1997, LSM lokal yang kelak bernama Latar Nusa memediasi bissu untuk pentas pertama kali di hadapan publik di Bali. Sejak saat itu, perlahan bissu mulai dikenal kembali dan mendapat tempat yang terhormat dalam masyarakat. Bahkan saat ini, Puang Matoa Saidi adalah bagian dari pementasan teater La Galigo untuk pentas keliling di panggung-panggung teater terkenal di dunia.
Uang hasil pentas keliling dunia yang diterima Puang Matoa Saidi itu kemudian dipergunakannya untuk melengkapi peralatan-peralatan dan untuk membiayai upacara-upacara bissu. Misalnya, acara mapparebba, upacara untuk pelantikan seseorang menjadi bissu. ”Saya sendiri tidak pernah diparebba oleh guru saya. Masse juga tidak pernah. Hanya Muharram. Uangnnya dari pentas La Galigo,” ujar Puang Saidi. Menurut tradisinya, seorang bissu harus memiliki seorang kader yang dididik secara khusus. Upacara mapparebba untuk Muharram, sang murid, berlangsung selama setengah bulan dengan biaya sekitar Rp50 juta, dilakukan pada tahun 2001 yang lalu.
“Dulu ketika masih zaman kerajaan, bissu punya tanah sendiri yang diberikan oleh kerajaan. Dari hasil tanah tersebutlah bissu mendapat nafkah. Namun saat ini, tanah tersebut sudah tidak ada,” jelas Amrullah. Menghilangnya sumber penghasilan menyebabkan bissu mencari alternatif lain. Seiring dengan meningkatnya persepsi masyarakat saat ini terhadap kelompok bissu, berangsur-angsur taraf kehidupan mereka mulai terangkat. “Tidak sempurna kalau ada pengantin, bukan bissu yang meriasnya,” ujar Muharram yang juga dikenal dengan nama Hasnah. Penghasilan sebagai indo botting (perias pegantin) biasanya digunakan membiayai upacara bissu yang penting.
Selain itu, kelompok bissu yang dipimpin oleh Puang Matoa Bissu juga sedikit demi sedikit mulai membuka beberapa upacara bissu yang dulunya sakral. Syaratnya, yang mengundang harus membiayai persyaratan-persyaratan upacara yang cukup besar serta sekadar uang honor yang sifatnya sukarela bagi yang berminat untuk menonton atraksi bissu tersebut.
Itulah juga yang kami lakukan ketika menyaksikan adegan terlukanya Puang Saidi. Sehabis menonton pertunjukan itu, saya tidaklah menganggap uang biaya upacara sebagai sesuatu yang mahal. Risiko yang dihadapi para bissu ini amatlah besar, sebagaimana terjadi pada Puang Saidi. Mungkin dengan alasan itu pula, dalam setiap pementasan teater La Galigo yang diikutinya itu, konon Puang Saidi terpaksa harus merelakan dirinya mengucurkan darah. Dan itu selalu terjadi, karena syaratnya tidak lengkap!
“Itulah, Nak, kalau sudah berjanji. Saya sudah tahu pasti akan begini,” kata Puang Saidi sambil sesekali meraba bekas tusukan di perutnya. “Tapi mau diapa, ini sudah janji saya kepada kita, ya risikonya harus saya tanggung sendiri”.[ASFRIYANTO]
Setelah sekian lama, ia keluar lagi. Keris itu masih tetap tertancap. Ketika Puang Matoa mencabutnya dengan sedikit memaksa, menyemburatlah cairan merah membasahi baju bissu keemasannya. Darah segar sepanjang kira-kira 7 cm itu menggumpal di ujung keris, dan segera dijilati oleh Puang Matoa. “Kejadian ini sering dialami oleh Puang Matoa, kalau syarat dalam melakukan upacara Mabbissu tidak lengkap,” ujar Amrullah, aktivitis LSM yang selama ini peduli masalah Bissu.
Dua jam sebelum peristiwa tersebut, di atas rumahnya yang tidak jauh dari Pasar Sentral Pangkep, Puang Saidi dengan pakaian putih-putih sibuk mengatur segala peralatan upacara dan sesajian yang akan dilakukakanya malam itu. Handphone bermerek yang dimilikinya selalu berbunyi. Dari pembicaraan yang terdengar, tampaknya ia sedikit marah. Ia bahkan mengancam seorang bissu di ujung telepon, agar segera datang. Bissu yang diteleponnya itu diperlukan kedatangannya untuk melengkapi syarat minimal jumlah bissu, agar upacara yang akan diadakan sebentar lagi bisa dimulai.
Sementara itu, Muharram, bissu termuda yang baru berusia 17 tahun tampak kecut di sudut ruangan. Ia lupa memakai tutup kepala dan masih berpakaian perempuan. Jemari tangannya bergetar saat menyusun tumpukan ketan tiga warna. Beberapa kali Puang Saidi memukul tangan Muharram ketika ia salah menyusun tumpukan ketan tersebut. Masse, bissu tertua yang ada di dalam ruangan tersebut, juga tampak tegang. Sesekali ia melongok ke luar jendela, berharap satu orang bissu yang sejak tadi ditunggu segera datang untuk meredakan kemarahan Puang Saidi. Namun yang ditunggu tidak juga muncul. Maka jadilah malam itu upacara mabbisu yang telah dijanjikannya tetap dilanjutkan, meski jauh dari syarat minimal.
Tidak seperti biasa, mereka tampak tegang. Kami para tamu yang tidak tahu menahu tentang soal itu malah duduk dengan tenang dan nyaman.
Lima belas menit pertama, Puang Saidi dan tiga orang bissu dengan pakaian berwarna keemasan dengan bilah-bilah keris panjang menari memutari sesajian di tengah ruangan. Alunan mantra mitis yang menggunakan bahasa To Rilangi – sejenis bahasa kuno Bugis yang hanya dimengerti oleh komunitas Bissu dalam memimpin upacara sakral – mengalun ditingkahi gendang. Ketika alunan gendang semakin keras dan cepat, gerakan para bissu tersebut semakin melambat. Terlihat jelas mereka mulai trance.
Muharram, sang bissu muda, kemudian mulai membuka gerakan maggiri yang pertama. Keris panjang yang terselip di pinggangnya dilepaskannya, dengan gerakan pelan mengikuti irama gendang. Keris tersebut ditancapkannya ke telapak tangannya. Walau ditekan berkali-kali dengan keras, keris itu tidak juga bisa merobek telapak tangannya. Bahkan ketika ia dibaringkan di tengah ruangan dan Puang Saidi kemudian menancapkan keris ke tenggorakannya, tak sedikit pun kulit leher Muharram tergores. Kuatnya tekanan keris Puang Saidi ke leher Muharram ditunjukkan dengan bunyi berderak pada tiang sandaran. Seketika saya bergidik. Para Bissu yang dalam kesehariannya feminim itu, tiba-tiba malam itu tampak gagah, jauh dari kesan lemah-lembut yang lekat dengan kehidupan kesehariannya.
Di tengah ruangan, upacara mabbissu semakin liar. Para bissu muda kemudian menyingkir ke sudut ruangan, menjaga dupa agar terus menyala. Tepat ketika harum cendana semakin menguat, Puang Saidi melangkah ke depan. “Adengan ini hanya untuk bissu yang sudah senior. Yang muda belum diizinkan untuk melakukannya,” ujar Amrullah menjelaskan.
Bersama dengan Puang Saidi, Masse ikut berputar-putar. Ia tampak gagah. Ia meletakkan keris ke lantai rumah, dengan ujung keris yang menghunus ke atas. Lalu Masse menjatuhkan dirinya ke ujung keris itu. Alas kayu yang dijadikan tumpuan kerisnya berderak patah. Gerakan ini ia lakukan berulang-ulang. Bahkan beberapa kali ia menjatuhkan dirinya dengan sangat keras.
Keramaian bertambah ketika dengan keris terhunus, Puang Saidi menggorok lehernya sendiri. Ia lalu menyandarkan ujung keris tersebut ke tiang rumah, dan menekan-nekankan keris tersebut ke lehernya. Bunyi gendang semakin kuat. Puang Matoa Saidi melenguh, ia kemudian menancapkan keris panjangnya ke bagian perut. Ia menghentakkannya ke lantai, dan seketika bambu yang menjadi alas kersinya patah. Ia semakin liar. Namun, ketika ia bangkit dan menghujamkan kembali keris ke perutnya, matanya mendelik. Masse dan Muharram di sudut ruangan memucat wajahnya. Puang Saidi sempoyongan, dengan langkah tertatih ia berbalik ke dalam ruangan. Bunyi gendang terhenti. Kami tersenyum puas dan bertepuk tangan. Namun, sekembali dari ruangan, Puang Saidi ternyata masih memegang hulu keris yang masih menghujam ke perutnya, berkali-kali jempol tangan yang telah diludahinya diusapkan ke bagian perut. Kami tercekat, perut Puang Saidi berdarah. Terlihat darah segar!
Satu minggu sebelum perisitiwa tersebut, kami telah melakukan survey kecil-kecilan tentang bissu dan tradisinya di Kabupaten Pangkep. Kami memilih komunitas bissu di daerah itu sebab keberadaannya sebagai salah satu kelompok bissu di Sulawesi Selatan cukup kuat. Kelompok bissu di Pangkep merupakan kelompok Bissu Dewata, yang secara hierarkis merupakan kelompok bissu dengan tugas religius yang penting. Kelompok bissu yang lain tersebar di Kabupaten Soppeng, Wajo dan Bone. Komunitas bissu di Soppeng dikenal dengan nama Bissu Pattudang, di Wajo disebut Bissu Paddupa, sedangkan di Bone disebut dengan Bissu Mappakasengeng. Nah pimpinan dari semua kelompok bissu tersebut bergelar Puang Matoa, yang saat ini dipimpin oleh Puang Matoa Saidi dari kelompok Bissu Dewata, Segeri, Pangkep.
Catatan arkeologis menguatkan bahwa komunitas bissu memiliki fungsi yang cukup penting dalam struktur kerajaan di Sulawesi Selatan pada masa lalu. Sisa-sisa makam bissu dan sumur bissu di berbagai daerah, semisal di Bulukumba, Sindenreng, Bantaeng dan Luwu, masih bisa ditemukan walaupun komunitas di daerah itu sudah tidak lagi mengenal bissu dan tradisinya. Hal itu terkait dengan penghancuran bissu beserta simbol-simbolnya oleh gerakan DI/TII.
Walaupun diberangus, bissu-bissu tua dalam penyamaran dan pelariannya tetap mempraktekkan “kebissuannya” secara diam-diam dan tetap melakukan proses pengkaderan. Puang Saidi misalnya, merasakan pengalaman terusir dari rumah dan lari berpindah-pindah dari Pangkep, Soppeng dan Bone. Ia menjadi bissu ketika berumur 25 tahun, tepatnya tahun 1974. Ia dididik oleh Sanro Saide (alm), seorang Puang Matoa Bissu yang tersisa. Dalam kehidupannya, ia mengalami operasi pemberantasan "penyakit masyarakat" oleh salah satu instansi dengan sandi “operasi tobat”. Namun ia berhasil lolos dari peristiwa tersebut.
Bissu mulai terlupakan oleh publiknya sendiri justru di tanah kelahirannya. Namun lewat catatan para peneliti asing, mulai zaman Mathes pada abad 19, sampai pada masa Pelras, Andaya, Gilbert Hamonic serta banyak peneliti lainnya, bissu mulai dikenal kembali. Ketertarikan mereka disebabkan karena bissu merupakan jejak dari agama-agama orang Bugis kuno yang bersumber dari ajaran La Galigo. Karena itu, sampai saat ini, bissu seperti Puang Saidi paling tidak mengenal tiga varian bahasa Bugis kuno, yakni bahasa To Rilangi (bahasa Bugis sakral untuk dewa), bahasa La Galigo (bahasa Bugis kuno) dan bahasa Bugis yang awam seperti saat ini.
Uniknya, walaupun dari banyak sumber peneliti menyebut mereka sebagai kelanjutan agama kuno orang Bugis jauh sebelum agama Islam dikenal, namun Puang Saidi akan sangat marah jika disebutkan bahwa upacara mabbisu merupakan bagian dari musyrik. Bahkan ketika ia mencoba menjelaskan makna cermin, ia mempersamakannya dengan istilah Nur Muhammad yang kerap digunakan oleh para sufi Islam. “Itu merupakan sinkritisme antara ajaran leluhur dan agama Islam di Sulawesi Selatan. Sekaligus membuktikan bahwa Islam ketika kali pertama datang telah merupakan bagian dari adat, simbolisasi betapa adat dan agama melebur menjadi satu yang kemudian menjadi bagian dari kebudayaan di Sulawesi Selatan,” jelas Halilintar Latief, salah satu pakar Bissu.
Lewat Halilintar pula, pada tahun 1997, LSM lokal yang kelak bernama Latar Nusa memediasi bissu untuk pentas pertama kali di hadapan publik di Bali. Sejak saat itu, perlahan bissu mulai dikenal kembali dan mendapat tempat yang terhormat dalam masyarakat. Bahkan saat ini, Puang Matoa Saidi adalah bagian dari pementasan teater La Galigo untuk pentas keliling di panggung-panggung teater terkenal di dunia.
Uang hasil pentas keliling dunia yang diterima Puang Matoa Saidi itu kemudian dipergunakannya untuk melengkapi peralatan-peralatan dan untuk membiayai upacara-upacara bissu. Misalnya, acara mapparebba, upacara untuk pelantikan seseorang menjadi bissu. ”Saya sendiri tidak pernah diparebba oleh guru saya. Masse juga tidak pernah. Hanya Muharram. Uangnnya dari pentas La Galigo,” ujar Puang Saidi. Menurut tradisinya, seorang bissu harus memiliki seorang kader yang dididik secara khusus. Upacara mapparebba untuk Muharram, sang murid, berlangsung selama setengah bulan dengan biaya sekitar Rp50 juta, dilakukan pada tahun 2001 yang lalu.
“Dulu ketika masih zaman kerajaan, bissu punya tanah sendiri yang diberikan oleh kerajaan. Dari hasil tanah tersebutlah bissu mendapat nafkah. Namun saat ini, tanah tersebut sudah tidak ada,” jelas Amrullah. Menghilangnya sumber penghasilan menyebabkan bissu mencari alternatif lain. Seiring dengan meningkatnya persepsi masyarakat saat ini terhadap kelompok bissu, berangsur-angsur taraf kehidupan mereka mulai terangkat. “Tidak sempurna kalau ada pengantin, bukan bissu yang meriasnya,” ujar Muharram yang juga dikenal dengan nama Hasnah. Penghasilan sebagai indo botting (perias pegantin) biasanya digunakan membiayai upacara bissu yang penting.
Selain itu, kelompok bissu yang dipimpin oleh Puang Matoa Bissu juga sedikit demi sedikit mulai membuka beberapa upacara bissu yang dulunya sakral. Syaratnya, yang mengundang harus membiayai persyaratan-persyaratan upacara yang cukup besar serta sekadar uang honor yang sifatnya sukarela bagi yang berminat untuk menonton atraksi bissu tersebut.
Itulah juga yang kami lakukan ketika menyaksikan adegan terlukanya Puang Saidi. Sehabis menonton pertunjukan itu, saya tidaklah menganggap uang biaya upacara sebagai sesuatu yang mahal. Risiko yang dihadapi para bissu ini amatlah besar, sebagaimana terjadi pada Puang Saidi. Mungkin dengan alasan itu pula, dalam setiap pementasan teater La Galigo yang diikutinya itu, konon Puang Saidi terpaksa harus merelakan dirinya mengucurkan darah. Dan itu selalu terjadi, karena syaratnya tidak lengkap!
“Itulah, Nak, kalau sudah berjanji. Saya sudah tahu pasti akan begini,” kata Puang Saidi sambil sesekali meraba bekas tusukan di perutnya. “Tapi mau diapa, ini sudah janji saya kepada kita, ya risikonya harus saya tanggung sendiri”.[ASFRIYANTO]