Kamilah mamak (paman) dari semua suku sejak dari hulu Kuantan sampai hulu Gangsal,” ujar Pak Katak dengan dialek Melayu yang kental. Selain sebagai kemantan atau dukun utama suku Talang Mamak, ia juga merupakan Batin atau kepala suku di pedalaman kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Provinsi Riau.Kuantan dan Gangsal sendiri adalah dua sungai purba yang masih mengalir sampai sekarang di Riau. Peran penting sungai ini pada masa lalu ditunjukkan dengan banyaknya reruntuhan situs masa Hindu-Budha seperti candi dan petilasan-petilasan purba yang tersebar di sisi kiri dan kanan tebing sungai. Cerita tutur masyarakat Talang Mamak dan suku-suku penghuni kawasan pedalaman Jambi dan Riau percaya bahwa dua sungai ini merupakan titik tolak peradaban mereka yang paling purba.
Namun saat ini kawasan kehidupan suku Talang Mamak telah jauh meningalkan dua sungai tersebut. Akibat perkembangan zaman, perlahan mereka terdesak jauh dan lebih ke pedalaman lagi menuju jantung pulau Sumatera yang saat inipun mulai tergusur oleh para pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan perkebunan kelapa sawit. Praktis di tengah pergulatan itu, sisa-sisa suku Talang Mamak saat ini hanya ditemukan di sekitar kawasan Taman Nasioanal Bukit Tiga Puluh saja. Hanya sedikit yang mau bermukim kembali di bibir sungai Gangsal, muasal kehidupan nenek moyang mereka.
Mengunjungi Pak Katak di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan perjalanan yang melelahkan. Izin harus diperoleh dari pengelola kawasan Taman Nasional di kota Rengat, ibukota kabupaten Inderagiri Hulu. Tanpa izin dari mereka, mustahil bisa memasuki kawasan ini dengan aman. Hal itu disebabkan, masih banyaknya binatang buas semisal harimau Sumatera yang lapar dan ancaman dari para pembalak liar yang akan sangat mungkin ditemui ketika memasuki kawasan itu.
Beredar cerita di kalangan para pendaki, para pembalak di kawasan tersebut tidak segan-segan membunuh orang asing yang memasuki kawasan hutan apalagi jika diketahui membawa kamera. Konon mereka, para pembalak itu juga mempersenjatai diri dengan senjata api. Karena itu, permohonan izin dari kantor taman nasional Bukti Tiga Puluh sekaligus juga berarti meminta pengawalan bersenjata untuk memasuki kawasan tersebut.
Dengan jagawana bersenjata, saya beserta rombongan dari mahasiswa jurusan sosiologi Universitas Riau memasuki kawasan tersebut dengan menggunakan mobil bergardan ganda.
Melewati jalanan bekas HPH dan perkebunan sawit merupakan pengalaman yang baru bagi saya. Walaupun dengan resiko, badan terasa nyeri terhempas kiri kanan ke lantai mobil pick up yang 100 persen besi itu, tapi saya senang, sebab kali ini saya terhindar dari berjalan kaki. Namun bayangan saya salah, bekas jalan HPH ternyata kerap mengundang longsor sehingga perjalanan dengan mobil, tidak lebih cepat jika dibandingkan dengan berjalan kaki.
Apalagi terkadang rombongan harus bersedia turun dari mobil, sekadar untuk mendorong ban mobil yang terjebak ke dalam lumpur atau untuk meringankan beban mobil ketika menyeberangi sungai kering ketika harus lewat titian kayu.
Mahasiswa sosiologi itu bercerita, pembalakan sangat marak terjadi di kawasan Bukit Tiga Puluh ketika reformasi bergulir. Dengan alasan kebebasan, perkebunan sawit milik putri mantan orang nomor satu di Indonesia dikapling-kapling, dan hutan pun dibabat. Semua itu dengan alasan reformasi yang disalahtafsirkan oleh masyarakat. Sehingga, bayangan akan lokasi suku Talang Mamak di hutan yang rimbun menjadi sirna dalam sekejap.
Namun dari bisik-bisik mahasiswa sosiologi di atas mobil, upaya pengawalan dari pihak jagawana pada dasarnya untuk mengawasi kami untuk tidak mengambil gambar di sembarang lokasi dan memastikan bahwa kami memang berfokus untuk menuju kawasan suku Talang Mamak saja. Karena itu saya menjadi paham, berulang kali beberapa dari petugas itu kerap mendelik atau mendengus ketika kamera mengarah ke tumpukan kayu dipinggir jalan yang kelihatan masih baru itu.
Setelah bersusah payah seharian, perjalanan kami terhenti. Tebangan kayu melintang di jalanan. Dari bekasnya, sepertinya pepohonan itu sengaja ditebang untuk menghalangi perjalanan dan itu merupakan tebangan yang baru berlangsung sekitar seminggu yang lalu. Panjang tebangan yang melintang jalan itu sekitar tiga kilometer.
Karena itu, berjalan kaki adalah alternatif satu-satunya untuk melanjutkan perjalanan menuju kampung Datai, kampung suku Talang Mamak yang masih berjarak sekitar 30 km. Dapat di tebak, setelah meninggalkan seorang jagawana yang tidak bersenjata, para jagawana lainnya kembali ke Rengat.
Bekas-bekas pembalakan menyisakan akibat yang luar biasa, walaupun pada peta rupa bumi yang saya pegang menunjukkan banyaknya sungai dikawasan ini, namun puluhan sungai-sungai dalam kawasan taman nasional saat ini telah mengering mengering. Ilalang telah menggantikan rimbunnya pepohonan, sehingga sinar matahari di kawasan yang persis tepat di jalur garis khatulsitiwa itu semakin terik saja.
Walhasil, walaupun jaraknya relatif tidak terlalu jauh, dan medannya relatif rata dibandingkan dengan kawasan Sulawesi, sisa perjalanan itu sungguh sangat berat untuk dilewati. Karena itu, dengan terpaksa, beberapa ransel atau bawaan lainnya ditinggalkan di tengah hutan, dengan harapan sesampainya esok di kampung Datai, sebagian orang Talang Mamak bersedia menjemputnya.
Malam, kami akhirnya sampai di kampung Datai. Letih dengan perjalanan seharian menyebabkan pertemuan dengan Pak Katak jadi terasa hambar. Walau demikian, saya masih menyempatkan diri menerima suguhan sirih dengan pinang muda yang di tawarkannya. Rumah Pak Katak yang kami tempati malam ini, merupakan bekas gereja yang dibangun oleh misionaris yang pernah berusaha menyebarkan injil ke dalam kawasan ini lima tahun yang lalu.
Karena itu, saya menjadi paham, di tengah hutan dengan akses yang jauh dari keramaian kota, rumah Pak Katak beratap seng, demikian juga dengan beberapa rumah lainnya. “Dia masok ke sini bao agamo, tapi awak di sini dak mau, kalau dah baagamo bukan lagi Talang Mamak tapi Melayu,” ujarnya. “Kalau ba agamo dak boleh tinggal, harus pegi dari kampong,” lanjutnya.
Walapun demikian, banyak juga orang Talang Mamak yang memeluk agama Kristen, tetapi tidak menjalankan ibadah seperti penganut agama Kristiani lainnya. Sebagian dari orang Talang Mamak, juga telah menganut agama Islam. Dengan agama yang satu ini, setidaknya hubungan sejarahnya lebih intim, sebab Kesultanan Rengat masa silam dan sampai sekarang masih merupakan tempat patron mereka dalam ritus.
Jadi, walapun sistem kesultanan sudah di hapuskan dalam negara kesatuan RI, mereka masih kerap membawa sesajian ke pinggir sungai Kuantan atau Inderagiri itu, dimana bekas lokasi istana Sultan Rengat masa lalu masih dingat oleh mereka. Bahkan Pak Katak sendiri, cukup awam dengan nama Nabi Muhammad, walapun dengan nama yang satu ini, bagi dirinya sudah dibalut dengan sinkritisme ritus dan mitos.
Tapi setidaknya, pengaruh ajaran Islam pernah cukup kuat di kawasan ini. Walaupun tidak semua warga memiliki KTP, namun jangan sesekali Anda meminta mereka untuk memperlihatkannya, sebab anda akan kaget dengan ulah pamong kita! Jangan kaget, entah diperoleh dari mana, yang jelas di KTP milik seorang warga yang bernama Cak Wing, tertulis : beragama Hindu!
Jauh dari hiruk pikik kota, orang Talak Mamak tetap saja belum tersentuh pembangunan. Bangunan sekolah berdinding bambu, telah rubuh 10 tahun yang lalu. Upaya pendidikan bagi anak-anak warga suku Talang Mamak justru diberikan oleh para pendatang semisal oleh Misionaris, LSM atau oleh mahasiswa yang berkunjung ke kawasan ini.
Awalnya, kegiatan pengajaran ini dipicu karena seringnya warga suku Talang Mamak ditipu ketika menjual karet atau getah jernang di pasar. Sejak saat itu, Pak Katak kerap meminta setiap LSM, Misionaris atau mahasiswa yang datang berkunjung ke Datai untuk mengajar masyarakat sekedar mengenali uang atau berhitung agar tidak ditipu ketika menjual hasil kebun mereka.
Jauh dari akses kota juga menyebabkan pemerintah dan dinas kesehatan terlambat untuk mengetahui, bahwa setahun yang lalu, wabah cacar telah membunuh lebih dari separuh anak-anak di kawasan ini, salah satunya adalah anak Pak Katak. Memang untuk menuju kampung Datai memiliki dua jalur alternatif, selain jalan darat tadi ada jalur sungai, yakni dengan menghulu sungai Gangsal. Melalui jalur sungai, menuju kampung Datai dari desa terdekat berjarak dua hari menghulu dengan rakit. Karena itu, dapat dimaklumi, petugas pemerintah mana yang berani mengambil resiko mempertaruhkan gaji untuk menghulu sungai Gangsal yang deras itu.
Terlebih lagi, hujan di hulu sepuluh tahun terakhir ini sulit diprediksi. Sebab hutan telah gundul. Karena itu, jika hujan sedikit saja di hulu, maka banjir besar di muara. Itu resikonya!
***
Ketika keesokan harinya, setelah mengitari kampung Datai bersama Pak Katak, suasana sepi begitu terasa. Para lelaki dan perempuan sedang sibuk mencari jernang, komoditi hutan yang berharga mahal, mirip dengan gaharu. Ada aura kemiskinan dari jejeran rumah di kampung itu pasca menipisnya hutan di sekitar kawasan adat Talang Mamak.
Mungkin ada benarnya juga, dalam satu kumpulan makalah konferensi masyarakat adat yang di adakan oleh salah satu LSM,yang bukunya ada ditangan saya, tertulis : Seringkali ketika suaka margasatwa atau taman nasional dibangun, pemerintah lebih memperhatikan satwa dan floranya dibandingkan dengan manusia yang menghuninya. Dan itu benar! Mereka, suku Talang Mamak di taman nasional itu bernasib serupa, padahal mereka bermukim di salah satu propinsi paling kaya di Indonesia.
Sementara itu, di tengah kebun kosong, para mahasiswa sosiologi Universitas Riau sedang mengadakan kelas darurat membaca dan berhitung bagi anak-anak suku Talang Mamak.
Saya dan Pak Katak kemudian ikut pula bergabung. Kelas darurat itu begitu interaktif, komunikasi dengan dialek Melayu antara mahasiswa itu dengan anak-anak Talang Mamak dan para orang tuanya begitu mengasyikkan.
Namun di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba saya menjadi terbahak keras, di ujung pertanyaan yang dilontarkan oleh para mahasiswa itu ”Siapo yang tau namo presiden Indonesia sekarang?” warga suku Talang Mamak itu hanya melongo. Ya, melongo! Tak ada jawaban![
ASFRIYANTO]
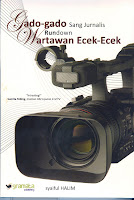 Buku ini laksana rundown sebuah program berita menjadi segmen per segmen. Segmen pertama menguraikan sepenggal perjalanan hidup yang berkaitan dengan profesi jurnalis televisi. Dari sekedar gila menonton televisi hingga menjadi mahasiswa. Selain mencoba membangun inspirasi dan kebanggaan akan profesi kewartawanan, segmen itu pun menguraikan sejumlah pengetahuan Dasar-Dasar Jurnalistik, Filosofi dan Sejarah Profesi Kewartawanan, Manajemen Media Massa, dan Penulisan Berita.
Buku ini laksana rundown sebuah program berita menjadi segmen per segmen. Segmen pertama menguraikan sepenggal perjalanan hidup yang berkaitan dengan profesi jurnalis televisi. Dari sekedar gila menonton televisi hingga menjadi mahasiswa. Selain mencoba membangun inspirasi dan kebanggaan akan profesi kewartawanan, segmen itu pun menguraikan sejumlah pengetahuan Dasar-Dasar Jurnalistik, Filosofi dan Sejarah Profesi Kewartawanan, Manajemen Media Massa, dan Penulisan Berita.














