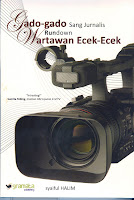Ketika menggarap musibah yang dialami almarhum Muhammad Guntur Syaifullah – kamerawan SCTV yang tenggelam bersama kapal Levina I – saya menampilkan simbol burung rajawali untuk menggantikan karakter almarhum. Kenapa harus sang raja burung? Kenapa harus bersimbol-simbol? Dan, kenapa jadi demikian “berat” di mata dan telinga?
Protes soal beratnya naskah episode “Kisah Sang Rajawali” memang harus diakui, sebagai kesengajaan. Pertama, untuk menghindari keseragaman dengan berbagai program lain, termasuk infotainment, yang ramai-ramai menggarap topik itu. Kedua, ini yang paling penting, karena topik kali saya dedikasikan untuk sahabat yang cukup sering berpatner dengan daya di lapangan. Sehingga, ketika ada protes kiri-kanan soal pesan yang demikian “berat”, ah biar!
Sumpah. Kali ini, saya tidak peduli kritik atau pujian apa pun. Namun, semua lillahi ta’ala, untuk menghormati perjalanan seorang sahabat ke alam baqa melalui karya.
Namun, tahukah bahwa tidak mudah bagi saya untuk memilih simbol itu ke dalam cerita. Tiga hari di lapangan, bergaul bersama masalah dan kepanikan teman-teman yang meliput atau ikut mencari, tidak mampu membangun kecerdasan. Dalam artian, tidak seperti biasa, saya tidak memiliki bekal premis atau ide cerita. Apalagi, struktur cerita berbentuk treatment script. Itu terjadi, karena hati sedang galau!
Di malam menjelang deadline, persis tengah malam, saya terbangun. Lalu, kumkum untuk berniat shalat tahajud. Saat mandi malam itu, di kepala saya terdengar lagu “Eagle and Horse”nya John Denver. Lirik dan melodinya menari-nari di kepala. Seketika, tanpa sadar, air mata membaur dengan guyuran air. Bahkan, dilatasi di rongga hidung tidak terasa lagi. Akhirnya, tangis di tengah malam meledak.
Tiba-tiba, saya ingat pernah berjalan bersama di pegunungan Tangkuban Perahu, Bandung, ketika meliput pelatihan SAR bersama rekan-rekan dari PT Dirgantara Indonesia. Meski agak berumur, ia terlihat tetap fit dan bersemangat mengikuti perjalanan.
Pada akhirnya, kelelahan memporak-porandakan kesabarannya. Ia sempat emosi dan naik pitam, ketika berdiskusi di tengah malam. Bahkan, ia sempat menantang berkelahi. Astaghfirullah.
Saya yang merasa lebih sadar, buru-buru minta maaf dan meredakan emosinya. Saya harus berada di depan soal kesabaran, karena sebagai reporter, saya bertanggungjawab untuk berbagai hal di lapangan. Saat itu, kami tidur berpisah. Namun, saya hanya berdoa, semoga saja, ia berubah. Karena, tidak ada persoalan besar yang harus dipertengkarkan. Diskusi recehan yang dibumbui kelelahan saja.
Meski peristiwa itu begitu membekas, dan sempat jadi perbincangan di kantor, ternyata kami bisa baikan kembali. Waktu, tanpa menunggu lama, ternyata bisa mengelus kesadarannya dan membuat lupa “cekcok” tempo hari. Kami berbaikan. Bahkan, saya menjadi kawan bicara pertamanya, ketika ia pulang dengan “cacad” dari liputan berdarah di Ambon. Dikatakan “cacad”, meski ia mempersembahkan gambar-gambar cantik dan momen dasyat, ketika emosinya tak terkendali, ia justru menuntut pulang.
“Cacad” itulah yang membuatnya terdempak dari percaturan para "rajawali", seakan ia bukan "rajawali". Padahal, hasil kerja di Ambon, tentu saja, kelas "rajawali". Bahkan, “cacad’ itu terus berbuntut pada nasib – gaji dan tunjangan lain. Subhanallah.
Luka itu saya dengar berkali-kali di telinga saya. Dan, sekarang, kembali terdengar seakan menjadi narasi dengan lagu “Eagle and Horse” sebagai musik latar. Dramatis. Beruntung tangisan itu hanya milik saya. Karena, istri dan anak-anak masih tidur.
Meski begitu, saya urung menggunakan lagu itu untuk POTRET. Karena, menghormati royalti dan proximity. Tiba-tiba, lagu “Rajawali” milik Kantata Takwa tiba-tiba mengemuka. Maka, saya langsung menulis sambil mengingat-ingat bait demi bait lagu itu.
Di paragraf awal saya tulis; rajawali adalah raja dari seluruh jenis burung di angkasa. Dengan sayap lebarnya, ia senantiasa menjelajahi seluruh ruang angkasa, untuk mengikuti kodratnya, hadir di bumi, mengisi sejarah kehidupan, dan bersiaga mencapai keabadian di alam kekal. Dengan cakar tajamnya, ia membuat sarang dan mencari makan, untuk menghidupi betina dan anak-anaknya.
Rajawali juga merupakan perlambang jiwa nan perkasa, tangguh, tak kenal lelah, dan merdeka. Ia bisa menjelma dalam diri setiap insan, karena anugrah kodrati atau tuntutan keadaan. Dan, ia bisa lahir dari trah mana pun. Bahkan, dengan kalangan sudra atau rakyat jelata. Dan, ia akan menjadi bagian dari sejarah agung, karena keperkasaan kepakan sayap dan cengkeraman jemarinya.
Cerita jurnalis dan sepotong berita adalah kisah rajawali dan sekerat daging. Ia akan menjelajah ke ruang angkasa mana pun, tanpa berpikir rasa lelah dan bahaya. Di benaknya hanya tersimpan sebuah keinginan, memenuhi rasa ingin tahu dan mengabarkannya untuk khalayak.
Seorang jurnalis, yang semula bisa saja berupa seekor burung nuri atau burung pipit, dalam beberapa saat, keadaan menuntutnya menjadi seekor rajawali. Dan, sang raja burung nan perkasa itu pun, senantiasa bersiap mencengkeram berkilo-kilogram daging di mana pun. Sayap-lebarnya akan terus mengepak menjelajah seluruh tempat kejadian. Dan, naluri membimbingnya untuk terus terbang, mencengkeram, pulang ke serang, dan kembali terbang.
Pameran metafora itu mengalir bukan tanpa kendali. Uraian filosofis rajawali saya dapati secara sempurna dari tujuh jilid buku “Syaikh Siti Jenar” karya Agus Sunyoto. Penempatan sang raja burung, dengan keperkasaannya, ketangguhannya, dengan maqom yang mesti didapatnya, sejujurnya ide penulis buku itu. Namun, saya meramunya sebagai bahasa televisi, sekaligus menempatkannya sebagai roh almarhum.
Pemilihan filosofi bercampur “pemaksaan” karakter semakin menjadi yakin, ketika saya melihat fakta nyata di lingkungan para “rajawali”. Saya kadang berpikir, lingkungan dunia jurnalistik tak ubahnya kerajaan burung. Karena, banyak spesies burung di lingkungan pekerjaan itu.
Bedanya dengan alam nyata, “kerajaan burung” nyata itu justru tidak dengan otomatis menempatkan rajawali sebagai raja para burung, meski di dalam kerajaan itu lebih banyak burung jenis itu. Lucu? Iya. Tapi, jangan tertawa. Karena, sesungguhnya menyayat kalbu.
Di “kerajaan burung” yang ditulis sebuah buku bertemakan inspiring stories, burung rajawali bisa menjadi raja. Burung gagak juga bisa menjadi raja. Burung beo juga bisa menjadi raja. Buruk merak pun bisa jadi raja. Pokoknya, burung apa pun bisa. Kecuali “burung” itu!
Maka, gemah ripah loh jinawi yang terlihat, tentu berbeda pula. Idealnya, yang menjadi raja di “kerajaan burung” berasal dari kalangan rajawali. Jadi, bila ini terjadi, ideal sekali. Tapi, bila dewa menghendaki gagak yang menjadi raja? Jangan heran, bila tiba-tiba gagak-gagak lain naik pangkat. Hakekat gagak yang cuma berteriak tanpa bekerja keras, liar, licik, dan rakus, ya tercermin di mana-mana. Akhirnya, burung-burung lain, siap-siap menjadi gagak juga atau terlempar ke sangkar kayu.
Sementara, yang dirinya merasa rajawali, siap-siap terbang tinggi untuk menghindari benturan atau merendahkan terbangnya agar bisa diraih sang raja. Lalu, merendahkan harga dirinya agak masuk dalam lingkaran sang raja. Rajawali yang merana, jadinya. Kalau memberontak, maka ia harus ikhlas terbang di luar lingkaran. Ya, rajawali liar jadinya.
Hasil akhir semua itu, amburadul! Jangan bicara sistem, aturan, norma, atau peraturan. Karena semua itu milik sang Gagak. Dia pasti betul. Apa yang diputuskan bawahannya pun pasti betul. Kita? Elu aja kali, gue nggak!
Kalau burung merak yang menjadi raja, maka suasananya jadi lain lagi. Karena, ia belum tentu akan merekrut merak-merak lain menjadi pendampingnya atau ikut naik jabatan. Tapi, burung-burung yang malas terbang, mulut dan kukunya tak tajam, bisa masuk barisan. Lho? Lha, kan merak hanya kepengin memamerkan bulu-bulunya. One man show, maksudnya. Orang lain nggak boleh. Nah, burung-burung lain, seperti pipit, nuri, atau cicakrowo, ya paling pas jadi pengikut setia. Sekaligus, jadi mentri-mentrinya.
Burung rajawali? Ya, bisa terbang setinggi-tingginya atau masuk kandang besi. Karena, terbang melayang sebebas-bebasnya bakal bikin gerah sang ratu. Atau, nanti dicurigai bakal makar. Maka, biar aman, ya masuk kandang saja. Biar saja ia menangis dan meraung-raung. Yang penting, sang ratu aman.
Walhasil, wal akhiri nasib para rajawali. Sistem, aturan, norma, atau apa lagi yang biasanya ada di lingkungan kerajaan, pupus sudah. Yang ada, ya wangi parfum bercampur asam kemenyan sang ratu. Maklum, sang ratu merokoknya kemenyan. Hi!
Kalau yang yang jadi raja burung beo? Ah, tebak sendiri alurnya. Atau, cari bukunya, deh. Salah-salah kutip, nanti malah dianggap bikin fitnah. Berabe, kan?
Supaya ngggak terlalu ngelantur, kita balik ke cerita penulisan “Kisah Sang Rajawali”. Di paragraf lain, saya menulis; Namun alam fana yang ditinggalkannya seakan tidak ikhlas. Ratusan burung-burung lain, termasuk juga Rajawali-Rajawali yang lebih gagah dan sakti, ikut larut dalam kesedihan. Entah karena merasa iba akan sejarah dan nasib sang rajawali, atau jangan-jangan, sekedar pura-pura simpati. Yang pasti, sanak-famili sang Rajawali merasa bersyukur, masih bisa melihat jasad sang Rajawali dan bisa berlama-lama memandang wajah agungnya.
Keharuan dan rasa iba terus berhamburan, tatkala jasad sang Rajawali diagungkan di hadapan burung-burung lain. Seiring dengan itu, ungkapan-ungkapan rasa duka pun tak henti terhembus ke udara, dan memayungi jasad sang rajawali. Pada hakekatnya, mangkatnya sang Rajawali bukanlah akhir dari kisah kehidupannya. Karena, ia hanya mengakhiri kodratnya sebagai umat di alam fana. Dengan begitu, ia pun berhenti membuat sarang dan mencari sekerat daging untuk sanak-familinya.
Selanjutnya, ia justru mendapati kehidupan lain yang lebih tentram, nyaman, dan abadi. Dan, bagi sang Rajawali, kematian justru merupakan pintu untuk menghantarkan jiwa perkasa, jiwa tangguh, jiwa tak kenal lelah, dan jiwa merdekanya, untuk menyatu dengan cahaya-Nya.
Semula kalimat yang dibold itu ada, tapi video editor justru merayu saya untuk menghapusnya. Khawatir ada yang tersinggung, katanya, nanti elo masuk kandang besi! Karena tidak berpikir apa-apa lagi, selain letih dan galau, saya setuju saja dengan pendapat itu. Yang penting, saya berhasil menuntaskan naskah dan bisa menyaksikan tayangan “berat” itu.
Pada akhirnya, dari cerita di atas saya ingin memberi gambaran, betapa sulitnya merangkai cerita untuk sebuah program. Meski sudah berada di lapangan tidak berarti akan mudah meramu ide, meluruskan teman, apalagi menjadikannya kerangka cerita. Bahkan, waktu yang mendesak pun bukan jaminan. Terlebih lagi, bila emosi terlalu bermain di dalamnya.
Maka, jurus memanfaatkan lagu-lagu populer memang tak bisa dihindari. Lalu, mengingat dan mengontemplasi buku-buku yang pernah dibaca, juga jadi jurus kedua yang perlu dimainkan. Dengan cara itu, kejaran deadline bisa teratasi dan program tetap bisa tayang. Selain itu, secara kulitas, paling tidak berbeda dibandingkan infotainment atau program lain yang digarap secara televisi. Yang paling penting, sebagai filmmaker, kita senantiasa dituntut menampilkan sesuatu yang berbeda dan fresh. Terlebih lagi, bila topik itu terlalu panas.[]
Note:
Tulisan itu didedikasikan setahun kepergian seorang sahabat, sang Rajawali, Muhammad Guntur Syaifullah. Semoga Allah SWT menyediakan tempat terindah di alam barzakh. Amien.
 Inayah Wahid: "Waktu ke Jombang, Gus Dur serasa diminta datang oleh mbah KH Hasyim Asyhari. Waktu di Jombang, sempat bilang ke sepupunya agar dijemput pada 31 Desember ini."
Inayah Wahid: "Waktu ke Jombang, Gus Dur serasa diminta datang oleh mbah KH Hasyim Asyhari. Waktu di Jombang, sempat bilang ke sepupunya agar dijemput pada 31 Desember ini."